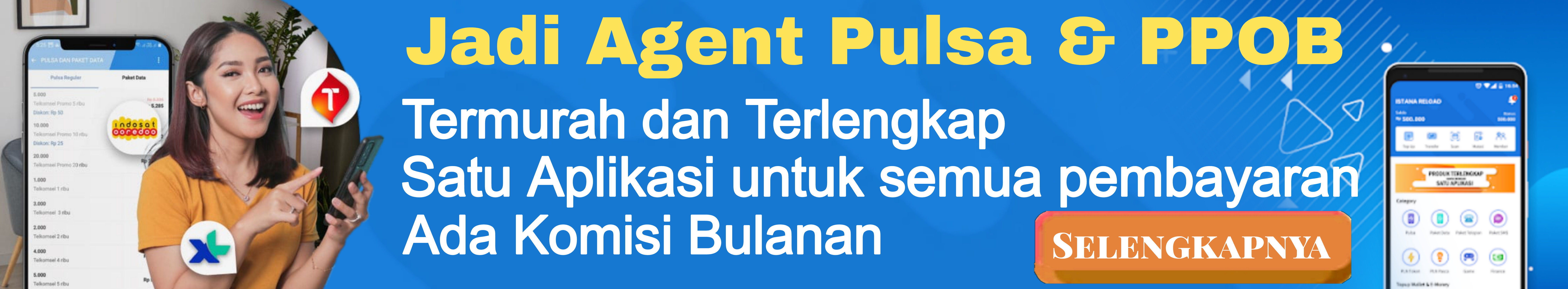|
| image: https://asset.sabdaliterasi.shop/img/Agama-dan-politik-identitas.webp |
Daftar Isi
Kepercayaan spiritual sering kali memiliki peran yang signifikan dalam diskusi tentang evolusi budaya manusia. Studi tentang masyarakat secara terus-menerus mempertimbangkan pengaruh dan status kepercayaan tersebut dalam evolusi kehidupan sosial.
Menurut pandangan Marx, agama bisa dijadikan instrumen untuk menciptakan kesadaran ilusif yang menguntungkan elit kapitalis dalam proses mempertahankan dan meningkatkan kekayaan mereka. Sebaliknya, Weber memiliki pendekatan berbeda. Dia meneliti bagaimana kapitalisme mula-mula berkembang di Eropa, mengidentifikasi moralitas Protestan sebagai elemen kunci yang membujuk individu untuk giat bekerja secara ekonomis, karena keberhasilan duniawi bisa diinterpretasikan sebagai indikasi penyelamatan di akhirat.
Nietzsche pernah berkata bahwa konsep Tuhan telah sirna di antara kerumunan di pasar, menandakan bahwa keberadaan religius kini kurang berarti dalam urusan ekonomi. Robert Wuthnow dalam "Religion’s Power: What Makes It Work" (2023) menyebutkan bahwa pengaruh agama kini ditafsirkan dalam kontras terhadap kekuatan-kekuatan duniawi. Sekulerisme merayakan konsep individu yang bebas berkemauan, sementara pada saat yang sama, individu itu dikendalikan oleh tatanan nilai yang mendorong patuh pada kekuatan supranatural.
Pendiri negara Indonesia berhasil mencapai kompromi elegan yang membebaskan negara dari konflik hebat antara agama dan sekulerisme. Dalam beberapa strata pemerintahan, Indonesia berhasil menegakkan hubungan simbiosis yang saling menghormati antara lembaga negara dan agama, terlihat jelas dalam regulasi perkawinan.
Sementara kebijakan politik kebanyakan berada di tangan pemerintah, dalam hal perkawinan, hukum ilahi masih diberi ruang untuk berperan, dan prinsip ini menjadi landasan dalam pencatatan sipil. Pengelolaan perkawinan di Indonesia merupakan contoh terbaik dari bagaimana negara ini telah menyelaraskan kekuatan-kekuatan keagamaan dalam berbagai aspek seperti ritual, organisasi, dan politik, sesuai dengan kategorisasi yang ditawarkan Wuthnow.
Pancasila dan Demokrasi: Keadilan untuk Identitas Inklusif
Di Indonesia, dekade terakhir menunjukkan fenomena menonjol terkait kekuatan agama dalam bentuk identitas dan wacana. Elemen-elemen diskursif—yakni praktik berbahasa yang memengaruhi persepsi dan pemikiran masyarakat—memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika sosial dan politik.
Dalam masa-masa awal pasca-kemerdekaan, Indonesia tercermin sebagai negara yang relatif berhasil merangkul keragaman dengan memadukan sekularisme dan nilai-nilai agama. Pendiri bangsa, melalui proses diskursif, mengatasi pembelahan identitas, yang sering kali berujung pada polarisasi, dengan membangun konsensus yang melintasi batas-batas agama dan kepercayaan.
Namun, era pasca-Reformasi tampaknya mengalami regresi. Identitas—khususnya identitas agama—telah dilekatkan pada arena politik tidak semata untuk diskusi dan refleksi bersama, namun lebih sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan elektoral dan legitimasi. Wacana politis di seputar identitas agama sering kali dibangun atas dasar emosi seperti ketakutan dan kemarahan, dalam upaya menciptakan solidaritas kelompok dan oposisi terhadap 'yang lain'.
Kekuatan wacana sangat bergantung pada kemampuan suatu pesan untuk bertahan dalam pendapat yang diterima oleh penerima pesan tersebut. Interpretasi dari wacana tersebut bervariasi, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan pendengar. Dalam konteks ketimpangan ekonomi yang tajam di Indonesia, di mana penguasaan sumber daya terkonsentrasi di tangan sedikit individu, realita ini dapat menjadi dasar bagi wacana yang memanfaatkan ragam identitas—termasuk agama—asalkan hal tersebut dapat mendorong agenda kelompok tertentu.
Dalam kaitannya dengan pembentukan identitas, kesalehan ritual dan politik yang berkembang saat ini merupakan refleksi dari praktik wacana. Yang mana identitas agama dan kesalehan sering kali dijadikan jembatan bagi suatu kelompok untuk menegaskan posisinya dan, pada saat yang sama, mengecualikan atau menyalahkan kelompok lainnya.
Dengan demikian, tantangan Indonesia adalah bagaimana mengembalikan fungsi wacana—terutama yang terkait dengan identitas agama—sebagai alat pemersatu dan bukannya pemecah belah. Kesadaran kolektif bahwa diskursus semacam itu dapat menuntun atau menyesatkan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan masa depan yang beradab dan bersatu untuk bangsa Indonesia.
Agama memiliki peran mendasar dalam pandangan psikososial masyarakat Indonesia, berpengaruh besar dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini membawa kemunculan pemimpin-pemimpin keagamaan yang berperan sebagai perantara antara masyarakat pemilih dan para kandidat politik yang mereka dukung.
Keadilan Bentuk Identitas Nasional Indonesia
Francis Fukuyama dalam karya "Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment" menjelaskan dinamika demokrasi yang paradoksal di mana, ironisnya, demokrasi yang membuka ruang untuk kebebasan berpendapat kadang memunculkan gerakan yang anti-demokrasi. Dalam konteks agama, ini berarti agama bisa menjadi sebuah identitas yang digunakan untuk menggalang dukungan bagi gerakan yang demokratis atau justru anti-demokrasi.
Fukuyama mengakui bahwa dalam demokrasi, gerakan yang berlawanan dengan status quo dapat muncul karena adanya kebebasan. Ini berbanding terbalik dengan sistem otoritarian di mana oposisi biasanya dibungkam. Di dalam evolusi demokrasi, Fukuyama yakin bahwa identitas "integratif" yang menyatukan bisa terbentuk, mengintegrasikan elemen-elemen yang bertentangan.
Di Indonesia, proses pembentukan identitas ini telah dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, di mana keadilan menjadi inti dari identitas bangsa. Ide keadilan ini masuk dalam filosofi Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan diteruskan dalam pasal-pasalnya. Konstitusi ini menciptakan koridor keadilan lintas generasi, memberikan perhatian pada pendidikan dan memberi peluang kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh mobilitas sosial melalui pendidikan.
Pendiri bangsa tidak hanya memikirkan kondisi semasa, tapi juga Indonesia yang akan datang—konsep keadilan yang inklusif dan berjangka panjang. Menghargai warga yang kurang beruntung serta memastikan pemberdayaan melalui pendidikan adalah bagian dari visi ini.
Indonesia telah memiliki kerangka untuk mengatasi politisasi identitas dan mempromosikan keadilan konstitusional jauh sebelum ide-ide Fukuyama dipopulerkan di abad ke-21. Implikasinya adalah, sesuai refleksi ini, Indonesia perlu kembali kepada prinsip-prinsip konstitusional aslinya untuk menjawab tantangan politisasi identitas yang semakin kompleks pada masa sekarang.