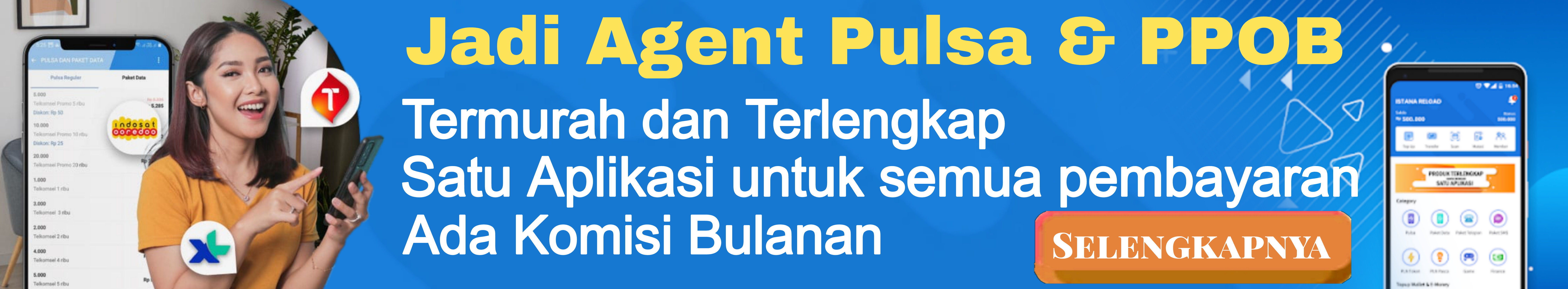|
| image: https://alif.id/wp-content/uploads/2018/11/harmonimedia.jpg.webp |
Daftar Isi
Dalam bidang studi ilmu politik, ide toleransi mengemuka sebagai topik yang cukup khas. Ini bertumpu pada pemikiran dari teoretisi politik yang berupaya merumuskan strategi ideal dalam membina suatu komunitas sempurna. Pembicaraan mengenai toleransi ini sering terlihat dalam konteks pemikiran filsafat dari tradisi Barat, di mana prinsip-prinsip liberalisme mendominasi.
Akan tetapi, menurut pandangan saya, konsep toleransi juga dapat dieksplorasi dan dianalisis melalui kaca mata dan praktiknya dalam filsafat politik Islam, terutama selama zaman kesultanan Ottoman dan filsafat politik di Eropa selama era pertengahan.
Tetapi, sebelum mempelajari bagaimana toleransi diwujudkan serta dipikirkan selama periode Ottoman dan zaman pertengahan, perlu sekali untuk memahami apa arti toleransi berdasarkan ilmu politik sebagaimana yang dijabarkan oleh Andrew Heywood, seorang cendekiawan politik terkemuka dan diakui di lingkaran akademisi politik setempat.
Heywood memahami toleransi sebagai suatu bentuk pengendalian diri yang melibatkan sengaja tak merespons secara negatif terhadap kepercayaan atau perilaku orang lain, meski terdapat perbedaan pendapat atau rasa tidak menyukai. Sikap permisif merupakan sikap yang lebih apatis, di mana seseorang umumnya tidak terlibat atau tidak peduli dengan kepercayaan atau tindakan orang lain.
Dalam konteks nilai-nilai liberal, toleransi tidak dianggap sebagai sikap yang bersikap netral; melainkan sebagai keberatan yang tertahan karena menghargai kebebasan orang lain. Dengan demikian, toleransi bisa diartikan sebagai pengakuan atas perbedaan kepercayaan dan perilaku orang lain, dengan cara tidak mencampuri atau memaksakan pandangan sendiri pada orang tersebut.
Pada masa yang sering dianggap sebagai zaman kegelapan, yaitu zaman pertengahan, pemikiran politik tentang toleransi telah muncul. Takashi Shogimen dalam karyanya "William of Ockham and Medieval Discourses on Toleration" menyatakan bahwa selama periode tersebut, ada tulisan-tulisan yang secara eksplisit menguraikan konsep toleransi.
John of Salisbury, dalam pemikirannya, mengakui bahwa keragaman pandangan adalah hal yang tak terpisahkan dari kondisi kemanusiaan, mengingat setiap manusia memiliki batasan dalam kapasitas berpikir.
Sementara itu, Nicholas of Cusa membahas toleransi dengan menyoroti isu rasial. Ia menganggap ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan ras dan mengusulkan sebuah gagasan cemerlang, yaitu universalitas Kristen, dengan harapan akan membawa toleransi yang menyatukan berbagai kelompok dalam kasih Kristiani.
Di samping itu, menjelang berakhirnya era medieval, John Locke muncul sebagai sosok yang pemikirannya terkemuka mengenai toleransi antaragama. Meskipun sering dihubungkan dengan periode Renaisans atau awal modern, nyatanya Locke adalah tokoh yang juga merintis jalannya pada zaman yang sering disebut sebagai zaman kegelapan.
Vicki Spencer, dalam karyanya yang bertajuk "Human Fallibility and Locke’s Doctrine of Toleration", menguraikan bahwa dinamika umum di Eropa kala itu ditandai oleh persaingan untuk memperoleh posisi dominasi antara golongan Protestan dan Katolik. Dinamika ini sangat terasa di Perancis, meskipun hadirnya Edict of Nantes yang seharusnya menjamin kebebasan beragama antara penganut Katolik dan Huguenot. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya usaha-usaha dari kedua belah pihak untuk mendominasi satu sama lain, yang salah satu indikasinya adalah gelombang migrasi besar-besaran menuju Belanda.
Terkait dengan kondisi tersebut, John Locke mempresentasikan pandangan bahwa toleransi tidak boleh hanya berada pada tataran minimal atau semata-mata formalitas. Locke menekankan bahwa toleransi harus menjadi bagian dari kewarasan pribadi seseorang dan harus terintegrasi dalam institusi-institusi gereja. Ini tercermin dari pernyataan Locke yang menyatakan bahwa toleransi merupakan ciri khas terpenting dari gereja yang sejati.
Pembahasan mengenai toleransi tidak hanya berlangsung dalam lingkup filosofi di Eropa pada zaman pertengahan, tetapi juga merambah ke ranah pemikiran politik Islam. Salah satu contoh menonjol dari pemikiran politik Islam ini dapat ditemukan dalam sejarah Kesultanan Utsmaniyah.
Keprihatinan saya terhadap topik ini mungkin dipicu oleh pujian yang diberikan oleh Voltaire. Sang filsuf terpukau oleh sikap toleransi di Kesultanan Utsmaniyah yang ia ungkapkan dalam karyanya, “Treatise on Toleration” yang dirilis pada tahun 1763. Voltaire menganggap sikap toleransi ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi intoleransi yang saat itu merajalela di Eropa.
Karen Barkey, dalam penelitiannya yang berjudul "The Ottomans and the Toleration" menjelaskan bahwa ketika Utsmaniyah meluaskan wilayahnya ke Balkan—sebuah kawasan yang sebagian besar penduduknya menganut agama Kristen—mereka menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai istimalet.
Kebijakan istimalet ini pada dasarnya menggambarkan kesungguhan Kesultanan Utsmaniyah dalam mengakui dan menghormati warga Kristen dengan berbagai bentuk regulasi yang inklusif. Salah satu kebijakan yang paling signifikan adalah memberikan kebebasan kepada pemuka agama setempat untuk mengelola urusan komunal mereka secara mandiri.
Kebijakan pajak dalam suatu daerah terkadang dialihkan kepada pemerintah setempat. Keadaan ini ditunjang oleh temuan Elias Kolovos yang mengungkapkan bahwa di bawah kepemerintahan Utsmaniyah, tokoh agama Ortodoks Yunani masih menikmati keistimewaan dalam hal ekonomi dan properti serta menjamin kegiatan keagamaan mereka dilaksanakan dengan bebas.
Sikap ini juga tercermin dalam pernyataan Sultan Suleyman I, yang dikenal sebagai "Suleiman yang Agung". Ketika ditanyakan perihal nasib umat Yahudi dalam kerajaannya yang berprofesi sebagai peminjam uang, ia mengajak para penasihatnya untuk memperhatikan sebuah vas yang berisi bunga-bunga berbagai warna dan bentuk, seraya mengingatkan bahwa keunikan setiap bunga—warna dan bentuknya—menambah kecantikan keseluruhan vas itu.
Dia kemudian menyatakan bahwa “dia memimpin beraneka ragam suku bangsa: Orang Turki, Moor, Yunani, dan lainnya. Setiap suku memberi sumbangsih pada kekayaan dan prestasi kerajaan. Dan untuk memelihara kebahagiaan bersama ini, dia bijak memilih untuk menghargai mereka yang telah berdampingan di bawah kekuasaannya.
Melihat contoh tersebut, kita bisa menarik pelajaran dari pemikiran politik dari dua era berbeda bahwa dialog tentang toleransi memang selalu ada dalam setiap masyarakat yang tercatat dalam sejarah. Bahkan di periode-periode yang dianggap suram, yang sering disebut sebagai 'zaman kegelapan' karena dianggap periode pengekangan bagi pemikiran manusia, diskusi tentang toleransi tetap ada sebagai nilai penting dalam kehidupan bersama.
Di sisi lain, jika kita meninjau filsafat politik Islam, khususnya selama pemerintahan Kesultanan Ottoman, kita akan melihat bagaimana toleransi berhasil menciptakan harmoni sosial yang berujung pada kemajuan peradaban. Cendekiawan Barat seperti John Locke dan Voltaire pun telah beberapa kali menyatakan kekagumannya terhadap praktik toleransi di Kesultanan Ottoman.
Kita bisa mengambil inspirasi dari sejarah untuk memecahkan masalah kontemporer tentang toleransi di Indonesia. Filsafat abad pertengahan dan prinsip-prinsip Kesultanan Ottoman mengajarkan pentingnya penerimaan dan keragaman. Contoh pemikiran dan kebijakan dari masa lalu dapat menjadi dasar pemikiran untuk membentuk masa depan yang lebih harmonis.
Indonesia, sebagai bangsa, dapat memetik pelajaran berharga dari pendekatan Ottoman. Konsep kesetaraan bukan hanya dalam segi prosedural tapi juga substansial, menunjukkan bahwa perbedaan dapat tidak hanya ditolerir tapi juga dirayakan. Seperti vas bunga yang keindahannya diperkaya oleh beragam warnanya, begitu pula kekayaan sebuah bangsa terletak pada ragam etnik dan agama yang saling bersinergi.
Harmonisasi antar-etnis dan agama, sebagaimana diungkapkan oleh Suleiman, bisa menciptakan simfoni sosial yang indah, di mana setiap suara dan nada memiliki tempat serta pentingnya masing-masing. Kita dapat mengarahkan resolusi kita ke arah pemeliharaan keragaman sebagai kekayaan bangsa, demi terciptanya suasana saling menghargai dan memajukan bangsa.